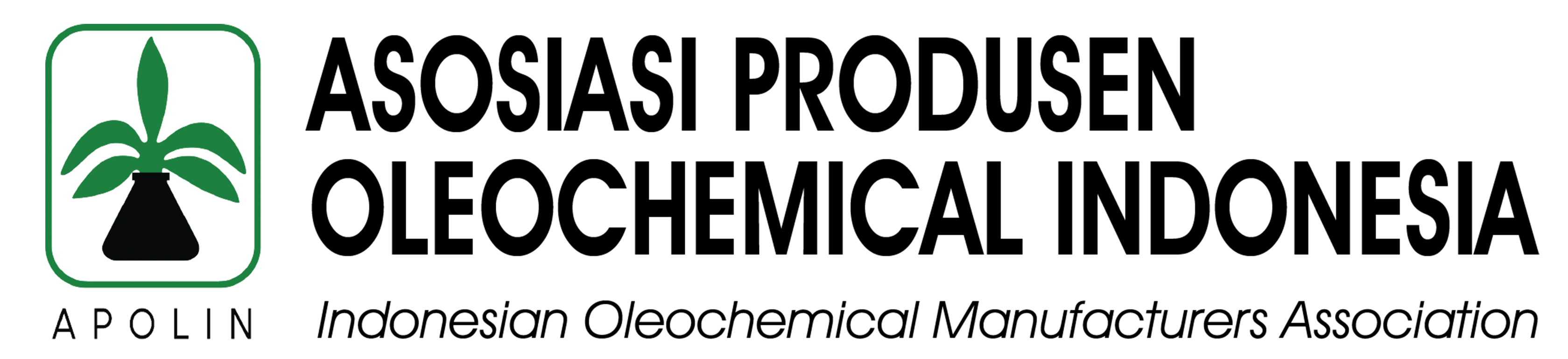PADI ditanam tumbuh ilalang. Peribahasa lawas itu cocok untuk menggambarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Seharusnya aturan ini menggembirakan karena mengangkat derajat kebijakan industri sawit dari sekadar peraturan Menteri Pertanian menjadi urusan Presiden. Tapi agaknya kenaikan derajat itu hanya gula-gula di tengah gempuran pasar internasional terhadap produk minyak sawit kita yang memble karena dituding sebagai biang deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Peraturan Presiden Nomor 44 tidak menjawab dua hal pokok dan krusial tersebut. Apa yang diatur dalam perpres tersebut hanya modifikasi minor dari peraturan Menteri Pertanian mengenai tujuh hal, yakni sertifikasi, kelembagaan, keberterimaan, daya saing, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi.
Problem utama sawit Indonesia adalah keberadaannya yang merusak hutan. Dari 16,3 juta hektare kebun sawit yang terdata oleh Kementerian Pertanian, sekitar 3,5 juta hektare berada di kawasan hutan. Artinya, kebun sawit tersebut hasil perambahan liar atau akibat kekacauan penerbitan izin antara pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan. Deforestasi dan degradasi adalah konversi hutan secara ugal-ugalan yang menjadi penyebab pemanasan global.
Dalam lima tahun terakhir, negara-negara yang mengikuti Konferensi Iklim dan menyetujui Perjanjian Paris 2015 sepakat bahwa apa pun kebijakan yang dibuat harus mengacu pada upaya pengurangan emisi, penyerapan karbon, dan pencegahan pemanasan suhu bumi. Sawit acap dituduh sebagai biang deforestasi karena sifatnya yang monokultur, lahannya hasil perambahan liar, tumpang-tindih dengan wilayah masyarakat adat, yang pada akhirnya mengakibatkan konflik sosial.
Pengabaian atas deforestasi dan hak asasi manusia justru akan makin merusak daya saing industri sawit Indonesia yang sudah babak-belur. Di tengah tuntutan dunia akan bahaya pemanasan global, kebijakan yang tidak pro-lingkungan membuat industri sawit makin tak kompetitif dan tak efisien. Akibat akhirnya adalah petani di lapangan tak mendapatkan efek pengganda dan “ekonomi menetes” dari kebijakan sawit ini.
Kita membutuhkan pemerintah agar aturan main dalam ekonomi dan sosial memiliki wasit yang imparsial. Tanpa standar dan aturan baku tentang rantai pasok sawit, tiap-tiap industri akan membuat aturan sendiri karena mengejar daya saing produk di pasar dunia, yang akan membuat ketimpangan dalam industri ini.
Pemerintah seharusnya memperbaiki problem di hulu industri sawit lebih dulu, yakni tumpang-tindih izin kebun sawit dengan kawasan hutan. Tanpa memperbaiki tata kelola sawit di lapangan, industri ini akan terus mendapat kampanye buruk sebagai penyebab deforestasi dan pemanasan global serta sumber malapetaka konflik sosial. Para ahli telah mengajukan pelbagai usul agar tata kelola sawit menjadi lebih pro-lingkungan.
Bagi industri yang kebunnya berada di kawasan hutan, penyelesaiannya melalui pengadilan. Sedangkan untuk kebun sawit oleh petani, penyelesaiannya melalui agroforestri. Dengan dua cara ituselain tujuh hal yang sudah diatur dalam perpresdaya saing minyak sawit kita akan naik karena sesuai dengan tuntutan pasar yang menghendaki prosesnya pro-lingkungan seraya menjunjung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akan sangat bijak jika Presiden bersedia merevisi Perpres 44.