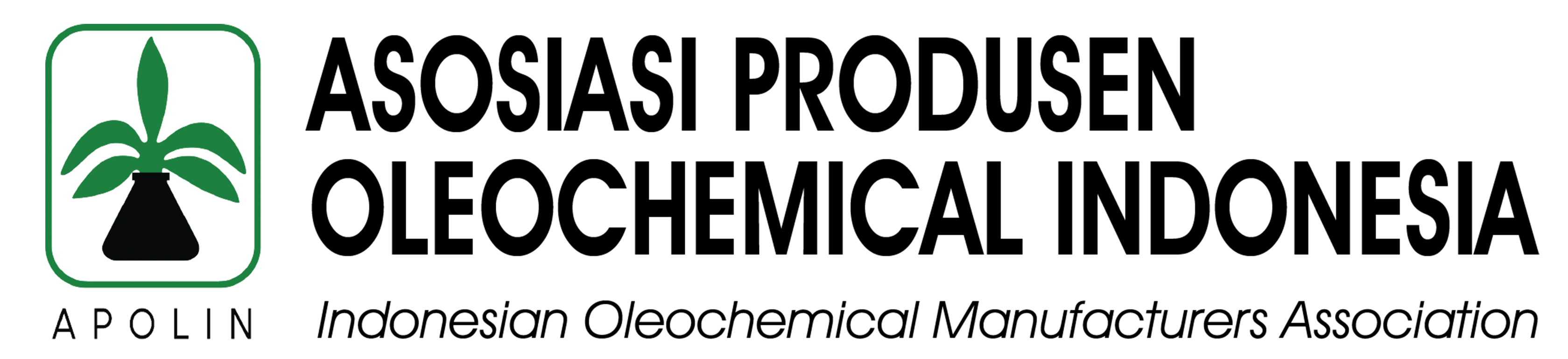Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (UE) pada Jumat (31/1/2020) setelah 4 tahun lalu warganya menghendaki itu lewat sebuah referendum dengan hasil ‘Brexit/Britain Exit’ dari keanggotaan di UE. Britania akan berjalan independen, terutama dalam urusan ekonomi yang membuat sejumlah perjanjian dagang dengan negara mitra bakal mengalami negosiasi ulang.
Namun, Profesor bidang Ekonomi King’s College London Jonathan Porters, dikutip dari npr.org, meyakini masa transisi Britania sangat beresiko tinggi di tengah perlambatan ekonomi global dan Eropa. Asumsi yang bernada pesimis setidaknya memang cukup banyak diungkapkan.
Apa akan ada negosiasi ulang perdagangan bebas Inggris-UE yang berujung kenaikan tarif atau pajak antar kawasan. Ini menjadi masuk akal bila negosiasi Inggris-UE tak menemui kesepakatan yang pasti. CNN melaporkan Britania harus menegosiasikan ulang perjanjian mereka dengan UE dalam kurun waktu 11 bulan sampai 31 Desember 2020.
Sampai pada titik ini, UE berada dalam situasi yang sama pusingnya mengingat lepasnya Inggris berpotensi mengguncang ekonomi negara-negara anggota, meski tantangan serupa membayangi Inggris salah satunya ketika ekonomi negara itu pada Agustus 2019 lalu menyusut sebesar 0,2%.
Begitu pun perjanjian dagang terhadap Indonesia. Isu terhangat soal pelarangan penggunaan produk CPO di UE melalui Renewable Energi Directive (RED) II nampaknya akan dinegosiasi dengan posisi yang kurang menguntungkan UE. Apakah ini berarti Inggris akan menerima CPO secara berbeda dibanding UE di dalam pasar mereka?
Terkait itu, CNBC Indonesia melaporkan bahwa Duta Besar Inggris untuk RI Owen Jenkins dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2020), mengatakan Inggris akan tetap menggunakan aturan UE dalam perdagangan kelapa sawit selama masa transisi.
Meski begitu, Indonesia sebagai produsen terbesar produk sawit dapat bernapas lega dengan keputusan Inggris. Setelah masa transisi Inggris mungkin akan menerapkan aturan berbeda. Jenkins mengungkapkan bahwa Inggris memahami pentingnya sektor kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah menggugat kebijakan RED II ke WTO pada 9 Desember 2020 dan diperkirakan berlanjut pada tahap konsultasi pada akhir bulan ini. Tuduhan Indirect Land Use Change (ILUC) dan deforestasi dari UE yang menjadi dasar pembatasan minyak sawit (CPO) memang telah mendapat perdebatan luas.
Untuk menepis kealpaan Indonesia terhadap lingkungan berkelanjutan (sustainable), Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah mendorong anggotanya menerapkan skema tata kelola sawit berkelanjutan lewat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak 2011.
Keluarnya Inggris dari UE memang tidak serta-merta menjadi guncangan hebat agar UE menarik tuduhan ILUC dari sawit. Namun, mencermati latar pemilih referendum Inggris yang memutuskan keluar dari UE, nampaknya hal itu menjadi alarm pengingat kepada UE untuk berhati-hatian menetapkan kebijakan yang sangat krusial bagi banyak orang di negaranya.
Lord Aschroft Polls yang mensurvey 12.369 pemilih menunjukkan hasil yang relevan terhadap kecemasan pada hilangnya kesempatan bekerja bagi mayoritas generasi tua yang berlatar pekerja. Hasil referendum menunjukan 51,9% warga memilih Inggris keluar dari UE, sebagian besar di antaranya adalah para pekerja penuh dan paruh waktu.
Ancaman imigran yang mengganggu kesempatan bekerja warga Inggris di negaranya sendiri bukan sebuah fenomena baru, namun semakin memuncak tatkala konflik yang mendera sejumlah negara di Timur Tengah.
Kondisi tersebut cukup menguatkan dalil yang dikampanyekan kelompok pro-exit saat itu. Situs voteleavetakecontrol.org memasukkan argumen bahwa hampir 2 juta orang datang ke UK dari UE (di tengah gelombang arus imigran Timur Tengah yang dicap sebagai negara miskin) sehingga ketakutan mereka bahwa masa depan Inggris akan dipengaruhi oleh negara-negara miskin.
Namun, poin utama dari fenomena ini menunjukkan bahwa UE justru kehilangan daya tawar akibat menghiraukan keadaan sosial yang sangat mendasar dari suatu negara yaitu hilangnya lapangan pekerjaan.
UE semakin terjepit untuk bisa meyakinkan kebijakan mereka yang terdengar sangat manusiawi dan menyenangkan banyak orang itu mampu terimplementasi terhadap realita masyarakat. Kenyataan bahwa ide yang sangat utopis namun dengan aturan yang kurang adil bagi sebagian besar orang dapat menurunkan kepercayaan terhadap UE.
Dan pertimbangan itu harus dipikirkan secara matang oleh UE ketika mereka mengusung isu lingkungan dan sustainable yang begitu ideal dan disetujui banyak orang, ternyata justru, dalam perkiraan yang sederhana, berpotensi memukul puluhan juta orang yang telah menggantungkan hidupnya dari pekerjaan yang diklaim ‘merusak lingkungan’. Dalam semangat berlainan dari itu, mungkin kita berpikir, “Apa sawit harus ditiadakan saja?”
Meski sebagian masyarakat Indonesia sepakat pada kemungkinan jawaban ‘ya’ dari pertanyaan itu, beberapa tahun mendatang ketiadaan solusi komprehensif untuk RED II terhadap Indonesia, akan mematuk lebih tajam sentimen masyarakat terhadap UE, terlebih dengan kecurigaan bahwa sesungguhnya ada motif di balik isu sustainable untuk melindungi produk minyak nabati UE.
Maka, ini bisa menjadi sedikit senyuman bagi kelapa sawit Indonesia, berharap UE sedikit melunak dalam mengencangkan kebijakan RED II dengan memperhatikan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan skema kelapa sawit berkelanjutan.